Five-in
Aku mengenalnya dua tahun yang lalu, setelah 1 tahun sebelumnya
aku hampir mati kerana cinta Daniel yang hilang. Aku yakin akan menutup pintu
hatiku selamanya saat itu. Namun apa iya? Aku salah. Sekarang dia hadir di
hidupku, mengisi hari-hariku, memberi kebahagian luar biasa yang tak pernah aku
dapatkan dari siapapun.
“Hay....,” teriak seseorang dari arah belakang. Aku tak peduli.
Aku hanya terpekur menatap lurus ke laut lepas. Membiarkan riak-riak ombak
bermain di antara mata kakiku.
Aku masih teringat betapa dengan mudah Daniel memutuskan
pertunangan kami. “Aku memiliki wanita lain” Ucapnya tanpa rasa bersalah. Aku
remuk. Dadaku seperti dihujam palu besar penghancur batu cadas para penambang
batu kapur di Gunung Pegat desa Babat Lamongan, namun palu itu terasa begitu
membara. “Kita putuskan semuanya saat ini” setelah itu dia pergi. Tak
mengucapkan kata-kata lagi. Bahkan untuk sebuah kata maaf sekalipun.
Tak ada satupun yang bisa aku lakukan saat itu. Bahkan
menangispun aku tak bisa. Air matkua sulit sekali mengurai, walau hatiku sudah
tak berbentuk sama sekali. Yang terjadi setelah itu, aku kolaps. Semua
pekerjaanku berantakan. Kesehatanku memburuk jatuh ke titik parah.
“Aku butuh istirahat Na,” Aku meminta izin pada Ana selaku
penanggung jawab di corporate kami untuk pergi menenangkan diri. “Aku butuh
waktu untuk sendiri” Ana tak bisa menolak. Dia tahu persis rekan kerja
sekaligus sahabatnya ini sedang dalam keadaan sangat tidak baik. Dia terpaksa
membiarkanku pergi menenangkan diri meski dengan kondisi kesehatan yang tak
bisa dibilang normal.
“Jika ada sesuatu, atau kamu butuh apapun segera hubungi aku”
ucapnya saat melepasku di stasiun Gubeng, Surabaya. Dia memelukku dengan erat seperti tak
ingin aku pergi. “Aku sudah meminta temenku yang ada di Bandung untuk menemani
kamu. Edy namanya, nanti dia yang akan membantu kamu selama berada di sana
Sepanjang perjalanan aku hanya bisa terpaku. Seperti mayat
hidup. Semua berkelebatan di benakku. Kenapa seperti ini? Apa salahku hingga
Tuhan menghukumku seperti ini? Kenapa aku selalu dibuang dan ditinggkan?.
Orang tuaku yang meninggalkan aku begitu saja tanpa mau tahu
lagi di mana aku, dengan siapa aku, atau masih hidupkah aku.
Kedua mbahku yang Dia panggil saat aku masih begitu membutuhkan
kekuatan untuk bisa bertahan hidup di dunia yang tak menerimaku. Meski aku
harus membayar penerimaan mereka dengan kerasnya perlakuan meraka terhadapku.
Paling tidak hanya mereka yang mau menerimaku.
Atau ketika sebuah tendangan dan caci-maki dari Paklek Mujib,
pamanku yang mengusirku dari rumah, juga tatapan sinis Paklek Amin dan Bulek
Ndalikah ketika melihatku memungut baju yang terserak karena mereka telah
membuangnya. Lalu sebuah senyum penuh ejekan dari Bulek Nuriyati, istri Paklek
Mujib yang memang tak pernah suka denganku.
Semua memenuhi memoriku. Mendesak-desak seperti ingin melompat
dan menertawakanku. Aku terseduh-sedan dengan air mata yang mengalir deras.
Membuat beberapa pasang mata yang berada di gerbong 3 kereta api kelas
Eksekutif, Turangga, menatapku antara
bingung dan iba. Aku tak perduli. Tak mau peduli. Aku hanya ingin semua cerita
ini hilang dari benakku. Dari hidupku.
Aku larut dalam kesedihan yang teramat dalam.
Jika ada orang yang benar-benar peduli dengan keadaanku,
merekalah ke empat sahabatku yang selalu bangga dengan apa yang aku lakukan.
Selalu memberikan semangat luar biasa sehingga yang aku rasakan tidak ada lain
selain kekuatan besar yang membuatku bangkit dari setiap keterpurukan. Merekalah keluargaku
yang sesungguhnya.
Mereka selalu mengatakan jika aku ini seperti rumput liar, yang
bisa hidup di manapun, bertahan dalam situasi apapun, dan menjadi pionir mahluk
hidup lain untuk sebuah ekosistem baru. Mereka adalah teman-teman terbaikku.
Kami bersama-sama membangun dengan susah payah sebuah corporate yang kini mulai
menjadi kebanggaan bagi kami. Five-in
Corporation, diambil dari keanggotaan kami yang lima
Kami bersahabat sejak sama-sama menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren
yang berada di desaku. Pondok pesantren yang mengajarkan kami banyak hal, yang
menghadiahkan kepada kami persahabatan indah ini. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah menjadi saksi persaudaraan di
antara kami.
Dengan kesamaan fisik yang sama-sama mungil waktu itu, membuat
kami terlihat selalu kompak ke manapun dan di manapun. Seperti kembar lima surat
Ana Fauziyah. Setelah lulus dari UNJ, dia memilih menemani
emaknya di kampung dan mengabdi di sana
Ana mengajarkan banyak hal untuk anak-anak di kampungannya.
Berbagai macam kerajianan tangan, pengolahan makanan, pemanfaatan sampah
menjadi produk trashion atau apapun
yang memungkinkan meraka bisa memberdayakan diri mereka sendiri kelak. Ana juga mengejarkan mereka menulis, karena
Ana memang suka menulis. Lalu bersamaku medirikan Five-in di Surabaya 3 tahun
yang lalu. Setiap satu minggu sekali dia pulang untuk melihat emak, bergantian
dengan kakak keduanya yang juga telah lebih memilih tinggal di dekat emak dan
meninggalkan pekerjaannya di Ibu kota
Maftuchatus Sa’adah. Kami memanggilnya Tucha. Diantara kami,
hanya dia yang telah menikah. Dipersunting seorang teman dari pesantren kami
dulu. Bahrul Chovi namanya. Mereka mungkin tak bisa dikatakan teman. Sama-sama
tak saling mengenal waktu itu. Peraturan pesantren yang memisahkan lokal putra
dan putri membuat kami tak bisa banyak mengenal santri putra. Tapi di sinilah
letak keunikan dan misterinya. Meraka pada akhirnya menikah. Dan kisah
percintaan mereka tetap menjadi rahasia bahkan bagi kami. Mereka bersepakat
untuk menutup rapat cerita cinta unik itu. “Untuk
konsumsi pribadi” kata mereka. Jika kami berkumpul, merekahlah yang sering
menjadi objek gurauan kami. Sering kali kami mengkompori tentang kisah cinta
monyet mereka masing-masing, dan kami menikmati sekali ketika mereka saling
bertanya dan menuduh.
Saidatul Maghfiroh. Saidah adalah yang paling istiqomah
menelateni kehidupannya di pesantren. Setelah lulus dari Aliyah, pendidikan
setingkat SMA dalam naungan yayasan yang sama dengan SMP kami, dia melanjutkan
pendidikannya di Perguruan Tinggi Swasta yang juga dikelola pesantrean sehingga
membuat pengurus yayasan mempercayainya sebagai salah satu pengajar di sana.
Namun di sisi lain, dia menyimpan satu opsesi untuk bisa lepas dan keluar dari
pesantren. Kami menebak mungkin ada sisi kebosanan yang dia rasakan. Saidah
selalu bertanya kapan kami akan mengajaknya untuk ikut marasakan kehidupan di
luar pesantren bersama kami. Dan ketika kami mengajakknya untuk bergabung dia
menyambut antusias dan mengatakan. “Kenapa ndak dari dulu?”
Icha, gadis imut, lebih imut dari kami berlima. Nur Hayatun
Anisa. Diapun sama dengan Tucha, sebentar lagi dia akan dipersunting oleh teman
waktu sama-sama nyantri di pesantren dulu, yang bahkan kisah cintanya tak
pernah kami duga sama sekali. Kisah cinta yang menurut kami tak biasa. Dia dan
calon suaminya sama-sama pendiam, sama-sama pemalu. Kemudian Reuni SMP kami
mempertemukan mereka di meja makan. Entah siapa yang memulai untuk saling
bercerita, yang pasti mereka sekarang memutuskan untuk sesegera mungkin
mengikuti jejak Tucha, membangun kehidupan pernikahan indah mereka. Luar biasa.
Dan aku, setelah berjuang sendiri lebih dari 3 tahun di Surabaya,
akhirnya aku mampu mendirikan sebuah usaha kecil di bidang fashion, terkhusus
untuk para muslimah. Dimulai dengan keisenganku membuat blog dan memasang
foto-foto yang aku ambil dari situs secara acak di internet. Hasilnya di luar
dugaan. Respon pasar sungguh luar biasa. Lalu dengan bermodalkan rekening
pinjaman dari teman satu kosku, aku membuka semacam Online Shop. Dan dalam waktu 3 tahun aku sudah mampu
mengembangkannya dengan mendirikan sebuah CV. Dengan brandku sendiri.
Dibantu dengan ke-empat sahabatku ini, kami mengembangkan
corporation kami di bidang industri Fahsion
kreatif. Kami memiliki beberapa item fashion di showroom kami, dan mengubah kiblat kami dari sekedar indusrti
fashion khusus untuk produk Gamis menjadi industri fashion center for Moeslimah. Kami menyebutnya demikian, meski
terkadang kami hanya mengarang saja untuk tema trend kami. Kami tak pernah
benar-benar mengerti tentang arah fashion yang sebenarnya.
“Asal ajalah, toh orang-orang juga ngak tahu kan
Keberadaan Daniel waktu itu membuatku memiliki semangat yang
lebih. Aku ingin dia bangga padaku. Aku ingin membuktikan, meski aku tak pernah
memiliki kesempatan untuk mencicipi bangku perkuliahan, tapi aku bisa
melepaskan diri dari stigma pembawa kutukan dari keluargaku. Aku harus bisa
membuat mereka melihatku sebagai seseorang. Daniel meyakinkanku jika aku bisa.
Namun ketika Daniel menghilang, semua menjadi berantakan. Aku
kacau, pekerjaanku keteteran. Posisiku sebagai pengawas pemasaran terpaksa
digatikan oleh Saidah yang harusnya memegang tim kreatif kami. Aku benar-benar
kolaps, dan meminta waktu untuk sendiri.
“Aku mau ke Pangandaran Na” mintaku pada Ana. Dia setuju, meski
dia tak mau jika aku pergi sendiri.
“Biarkan aku sendiri dulu Na, semua akan baik-baik saja” Aku
meyakinkan Ana. Ana terpaksa setuju, begitu pula teman-teman yang lain. Mereka
tahu aku memang butuh waktu untuk bisa sendiri. Semua sadar jika ini begitu
berat bagiku.
Aku memilih Pangandaran sebagai tempat merenungku. Sebuah tempat
yang aku sendiri tak pernah tahu keberadaannya. Aku hanya mendengar ceritanya
dari Daniel. Katanya, Pangandaran adalah surganya keindahan di Jawa Barat,
tempat Daniel berasal. Di Pangandaranlah tempat yang kami rencanakan untuk
menghabiskan liburan bulan madu kami. Danielpun mengatakan jika kami bisa
melihat matahari terbit dan tenggelam dari satu tempat.
“Kita seperti menyaksikan perputaran hari di sana
Menghentikan hari hanya tinggal cerita. Atau mungkin saja Pangandaran
memang akan menghentikan perputaran hari untukku, dengan kematianku. Aku
semakin terisak. Membuat penumpang lain menatapku penuh tanya, namun tak ada
yang bertanya, mungkin mereka tahu jika aku sedang sangat terluka, dan mereka
lebih memilih untuk membiarkan aku larut dalam tangisanku. Sendiri.
Pangandaran, aku tak ingin mengehentikan
harimu, tetaplah berputar se arah porosmu, biarkan semua tetap seperti titah
Tuhanmu, sesuai peredaran mataharimu yang cantik. Aku hanya ingin melihatmu
sebagai janji pada cintaku yang telah hilang, sebagai pengobat untuk luka yang
saat ini mengangah dengan lebarnya. Semoga kamu bisa mengerti.
“Hay.., awaaass”seoarang berteriak seperti meneriakiku. Aku tak
ingin peduli, namun teriakannya yang terus menerus membuatku terusik. Dan
ketika aku menoleh, orang-orang di bibiran pantai terlihat kecil dan jauh.
Mereka melambai, menunjuk-nunjuk mungkin juga berteriak ke arahku, tapi aku tak
bisa mendengarnya. Ombak Pangandaran bukan lagi berlari-lari di mata kakiku,
tapi hampir menenggelamkanku. Aku tersengal-sengal. Nafasku naik turun.
Kepalaku timbul-tenggelam di permainkan ombak Pangandaran.
Pangandaran, apakah aku bisa membuatmu
menghentikan hari. Untuk hari ini saja. Atau aku benar-benar akan mati di sisimu.
Kesadaranku mulai hilang. Aku merasakan paru-paruku penuh dengan
air. Aku seperti tercekik. Nafasku tersengal-sengal kian berat. Dan di saat
antara hidup dan matiku aku seperti melihat bayangan seseorang mengulurkan
tangannya untuk menuntunku. Dia tersenyum dengan manis. Matanya seperti
mengatakan jika aku akan baik-baik saja.
“Daniel” bisikku lirih.
“Apa aku akan mati Daniel?” Aku hanya bisa melihat gelap yang
pekat, namun tidak dengan wajah itu. Wajah itu seperti bercahaya dalam
kegelapan. Wajah itu terus memberiku keyakinan jika aku akan baik-baik saja.
“Daniel, kau kah itu?” Aku mencoba meraihnya di tengah
kepayahanku melawan cekikan ombak Pangandaran. Diapun meraihku, memelukku,
seperti ingin memberiku perlindungan dalam dekapannya, “Jangan tinggalkan aku”
Aku terisak di pelukannya,
“Aku tidak akan pergi sayang,” ucapnya. Dia terus mendekapku
erat. Lalu mendekatkan bibirnya ke bibirku. Aku terpejam, mencoba memberikan
bukti cinta yang pernah dia minta. Aku tak ingin kehilangannya lagi. Aku tak
ingin melepaskannya, selamanya.
Dan ketika aku membuka mata, semuanya tiba-tiba menjadi sangat
silau. Pangandaran yang ganas sepertinya telah melepasku. Aku seperti sedang
bermimpi. Bermimpi Daniel kembali padaku, menatapku, memelukku dan menciumku.
Tapi mimpi itu sepertinya masih bisa aku rasakan. Aku masih bisa merasakan
hangat cuiman yang dia berikan. Aku mencoba bersahabat dengan benderang yang
tiba-tiba. Aku buka mata sedikit demi sedikit, lalu menyaksikan beberapa orang
mengerubungiku. Aku merasakan seseorang memegangi kepalaku, membuka mulutku
dan,
“Apa-apaan ini?” Aku
tersentak. Seseorang menciumiku di depan umum saat aku tidak sadarkan diri? Aku
muntab. “Kamu gila ya?” sekonyong-konyong aku mencoba berdiri. Memaksakan diri
untuk bangkit dan melihat siapa yang sudah kurang ajar terhadapku.
“Kamu yang gila” seorang pemuda berbalik membentakku. “ Kamu mau
mati ya?” sentaknya lagi. Entah kenapa aku reflek menggeleng “Ombak sedang
pasang dan kamu terus berjalan ke tengah, kalau tidak mau mati mau apa? Kalau
mau bunuh diri jangan di sini non, merusak pemandangan”
Aku terisak. Kenapa orang ini memarahiku? Aku tak pernah
bermaksud membunuh diriku, semua terjadi di luar kontrol. Aku terseduh dan
terus menagis, lalu luruh terduduk di pasir putih Pangandaran. Rupanya hal itu
membuat pemudah di depanku luluh, tak lagi membentakku, mungkin dia sadar telah
berkata terlalu kasar padaku.
Dia berjongkok di hadapanku. “Bukan begitu cara menyelesaikan
masalah” Dengan lembut dia memapahku, mengantarkanku ke penginapan tempatku
menginap dan menitipkan aku ke resepsionis lalu melangkah pergi.
“Tunggu” Dia mengehetikan langkahnya.
“Iya?” jawabnya.
“Terima kasih,” ucapku tulus.
“Sama-sama” jawabnya
dengan seulas senyum yang pernah aku kenal, tapi entah di mana.
“Nama kamu siapa?”
“Aku Lugina, panggil saja Ugi”
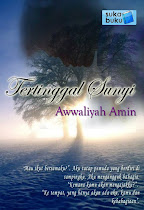



Tidak ada komentar:
Posting Komentar